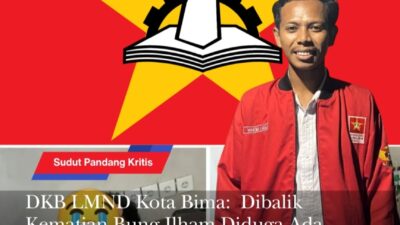Bima, 15 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) Ntb – Selama bertahun-tahun, Kecamatan Lambitu tak pernah absen dalam menyuarakan satu hal yang paling mendasar: perbaikan infrastruktur jalan. Dari Musrenbang tingkat desa hingga kecamatan, bahkan ketika aspirasi itu dibawa ke Musrenbang Kabupaten, suara masyarakat tetap konsisten, bulat, dan tegas jalan adalah kebutuhan utama, bukan sekadar permintaan. Namun di tengah konsistensi rakyat ini, pemerintah justru menunjukkan ketidakkonsistenan dalam mendengar. Tahun berganti, proposal diajukan, forum difasilitasi, berita ditulis, dan fakta disodorkan. Tapi jalan tetap rusak. Pemerintah tetap diam. Seolah suara Lambitu bukan suara rakyat, melainkan derau yang layak dibungkam.
Inilah puncak dari kedangkalan birokrasi dan pragmatisme kekuasaan yang telah menjangkiti sistem anggaran Kabupaten Bima. Di tengah demokrasi yang mengklaim partisipasi publik, Lambitu justru menjadi contoh bagaimana partisipasi rakyat dilembagakan untuk disimbolkan, bukan untuk ditindaklanjuti. Musrenbang hanya menjadi ritual tahunan, bukan ruang pengambilan keputusan yang nyata. Aspirasi masyarakat Lambitu dikumpulkan, didokumentasikan, tapi tak pernah diwujudkan. Ia jadi catatan pinggir, bukan agenda utama.
Apa yang terjadi pada masyarakat Lambitu hari ini adalah pengkhianatan terhadap hak politik mereka. Hak untuk ikut menentukan arah pembangunan daerah. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di mata anggaran. Hak untuk tidak dijadikan korban statistik. Pemerintah Kabupaten Bima dan DPRD-nya gagal menunjukkan keberpihakan yang konstitusional. Mereka lebih sibuk menghitung suara daripada menghitung penderitaan. Mereka lebih memilih membangun berdasarkan suara mayoritas daripada kebutuhan minoritas. Dan selama pendekatan pembangunan seperti ini terus berlangsung, maka Lambitu akan tetap menjadi luka di tubuh kebijakan daerah.
Bukan karena Lambitu tidak bersuara. Tapi karena suara mereka sengaja dimatikan. Bukan karena masyarakat tidak tahu cara memperjuangkan aspirasinya. Tapi karena sistem yang mereka hadapi telah mengerdilkan aspirasi itu menjadi sekadar daftar yang bisa ditolak dengan satu kalimat: “Belum ada anggaran.” Padahal setiap tahun ada anggaran. Yang tidak ada hanyalah keberanian politik untuk membagi secara adil.
Lambitu tidak pernah kurang dalam kontribusi. Yang kurang adalah pengakuan. Dan selama pemerintah menolak untuk mengakui mereka sebagai bagian dari rakyat yang layak mendapatkan pembangunan, maka sesungguhnya kita tidak sedang menghadapi masalah infrastruktur. Kita sedang menghadapi krisis etika dalam tata kelola anggaran. Jalan rusak hanyalah gejala dari penyakit yang lebih dalam: hilangnya komitmen negara terhadap suara yang berasal dari tempat terpencil.