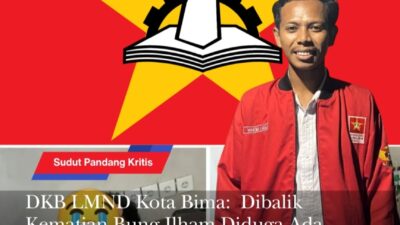Bima, 17 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) NTB – Di tengah riuhnya janji-janji pemerataan dan sorak-sorai pembangunan yang kerap digaungkan, kisah Lambitu terhampar sebagai monumen bisu atas ironi demokrasi. Lebih dari dua puluh tahun, enam desa di kecamatan terpencil ini terhuyung dalam lumpur dan batu, bukan karena tak ada dana, melainkan karena suara mereka tak cukup “nyaring” untuk terdengar di tengah bisingnya kalkulasi politik. Lambitu, dengan segenap kerentanan geografis dan demografisnya, telah menjadi korban nyata dari logika politik yang mengukur keadilan dengan timbangan elektoral.
Realitas jalanan Lambitu yang tak kunjung tersentuh aspal adalah narasi kelam tentang bagaimana birokrasi, yang seharusnya melayani, justru menjadi tembok tebal yang membungkam hak-hak dasar warganya. Masyarakat Lambitu tidak pasif. Mereka bukan golongan yang hanya menunggu uluran tangan. Setiap tahun, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa hingga kabupaten, jeritan mereka tentang akses jalan yang layak selalu menjadi prioritas utama. Proposal disusun rapi, argumen disampaikan lugas, dan harapan dipanjatkan tulus. Namun, alih-alih direspons dengan tindakan nyata, suara-suara itu hanya berujung menjadi deretan arsip, formalitas prosedural yang tak berujung pada kebijakan konkret. Seolah partisipasi publik hanya sebuah pertunjukan tanpa konsekuensi kebijakan yang berarti.
Ironisnya, alasan di balik pembiaran ini jauh lebih kejam dari sekadar ketiadaan anggaran. Ini adalah soal politik jumlah. Dalam peta kekuasaan Kabupaten Bima, Lambitu dianggap sebagai wilayah yang “tidak seksi” secara elektoral. Jumlah penduduknya yang sedikit, desa-desa yang terpencar, dan kontur geografis yang menantang, membuat mereka dipandang sebagai investasi pembangunan yang mahal namun tidak menjanjikan keuntungan suara signifikan. Bandingkan dengan Desa Ngali di Kecamatan Belo, misalnya, yang dengan populasi melampaui seluruh penduduk Lambitu, justru selalu menjadi prioritas karena dianggap lumbung suara. Ini adalah cermin bagaimana kebijakan anggaran di Kabupaten Bima dipandu oleh logika pragmatis elektoral, bukan prinsip keadilan dan pemerataan yang semestinya menjadi fondasi pembangunan nasional.
Ketika Geografi Dijadikan Dalih untuk Pembiaran
Kondisi geografis Lambitu yang sulit – jalanan terjal, jurang menganga, dan lumpur pekat di musim hujan – seharusnya menjadi alasan kuat bagi negara untuk hadir lebih intensif. Namun, kenyataannya justru terbalik. Tantangan geografis ini seringkali disulap menjadi dalih pembenaran untuk tidak mengalokasikan anggaran pembangunan. Jalan yang rusak parah bukan lagi hanya soal kenyamanan; ini adalah hambatan fundamental bagi akses pendidikan, pergerakan ekonomi, dan yang paling krusial, layanan kesehatan darurat. Ketika ambulans tak mampu menembus genangan dan lumpur untuk menjangkau pasien, ketika anak-anak harus bertaruh nyawa di jalan setapak demi mencapai sekolah, maka yang sesungguhnya tergelincir bukan hanya kendaraan, melainkan janji konstitusi akan hak atas kehidupan yang layak.
Menguak Luka Sistemik: Demokrasi Tanpa Keadilan
Narasi pembiaran Lambitu ini bukan sekadar insiden sesaat, melainkan pola berulang yang mengakar dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ini adalah bukti nyata dari watak kekuasaan yang cenderung melihat wilayah pinggiran sebagai beban, bukan sebagai warga negara yang berhak atas pelayanan publik yang adil. Jalan di Lambitu tidak hancur karena alam membangkang; ia hancur karena kebijakan membiarkannya hancur. Setiap lubang di jalanan itu adalah pengingat betapa rapuhnya legitimasi kebijakan publik yang mengabaikan suara-suara minoritas demi keuntungan politik sesaat.
Kisah Lambitu adalah tamparan keras bagi diskursus pembangunan yang mengedepankan efisiensi elektoral di atas nilai kemanusiaan. Ini adalah panggilan untuk kita semua, bahwa selama pemerintah daerah masih menggunakan jumlah penduduk sebagai alat seleksi anggaran, maka di sanalah letak kekejaman paling sunyi dari sistem politik lokal kita. Lambitu tidak kekurangan suara; mereka hanya kekurangan pendengar yang tulus. Dan selama lumpur masih menyergap, kendaraan masih tergelincir, dan harapan rakyat masih tenggelam di lubang jalan, maka sesungguhnya yang sedang tergelincir adalah keadilan itu sendiri.
Apakah kita akan terus membiarkan politik jumlah meninggalkan luka yang menganga pada demokrasi kita, ataukah saatnya bagi kita untuk menuntut keadilan bagi Lambitu dan wilayah-wilayah “terlalu kecil” lainnya?