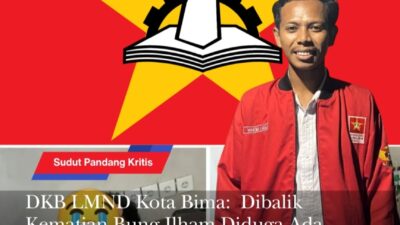Bima, 15 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) Ntb – Di tengah gempita janji pembangunan, Kecamatan Lambitu justru menjadi medan sunyi yang menunjukkan betapa suara rakyat bisa kehilangan makna saat berhadapan dengan politik anggaran yang selektif. Setiap tahun, dari desa Kaboro hingga Kaowa, warga dengan penuh keteguhan menyalurkan satu tuntutan utama lewat forum Musrenbang: perbaikan jalan. Permintaan itu tak pernah berubah bukan karena warga minim gagasan, tetapi karena jalan rusak tetap menjadi ancaman utama bagi keselamatan, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan mereka. Namun ketika suara itu dibawa naik ke forum Musrenbang Kabupaten, yang terjadi bukanlah pengambilan keputusan, melainkan pengabaian yang kian brutal.
Pemerintah Kabupaten Bima yang semestinya menjadikan Musrenbang sebagai kompas penyusunan anggaran justru menjadikan suara Lambitu sebagai repetisi tahunan yang hanya ditanggapi dengan retorika. Setiap proposal masuk, setiap perwakilan bicara, tapi jalan tetap penuh lubang, genangan air tetap menghuni ruas-ruas penghubung antar desa, dan lumpur tetap menelan harapan. Lambitu tidak diam, tapi sistem memilih untuk tidak mendengar. Musrenbang di Lambitu gagal bukan karena warganya tak berpartisipasi, melainkan karena hasil partisipasi mereka tak pernah diberi legitimasi anggaran.
Inilah potret kebijakan yang membajak demokrasi partisipatif menjadi ritual birokrasi tanpa makna. Pemerintah seolah hanya mendengar suara yang menguntungkan secara elektoral. Wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk besar dan daya tawar politik tinggi lebih mudah mendapatkan alokasi anggaran. Sedangkan Lambitu dengan penduduk tak lebih dari empat ribu jiwa dan desa-desa yang saling berjauhan dianggap tidak menguntungkan secara kalkulasi. Maka permintaan mereka, betapapun rasional dan mendesak, selalu kalah dalam proses penganggaran.
Setiap lubang di jalan Lambitu adalah bekas luka dari sistem yang mendengar bukan dengan hati, tapi dengan kalkulator. Dan selama pemerintah hanya menjadikan partisipasi sebagai formalitas, maka kita tidak sedang berbicara tentang kegagalan teknis, melainkan kegagalan politik. Jalan rusak yang bertahan selama dua dekade adalah bukti bahwa suara rakyat kecil bisa dimanipulasi, dikecilkan, bahkan dipadamkan dalam ruang publik yang seharusnya milik semua.
Lambitu telah membuktikan bahwa mereka tidak kurang bersuara mereka hanya terlalu jujur dalam menyuarakan kebutuhan. Dan untuk itu, sistem justru menempatkan mereka di baris terbelakang. Ketika demokrasi tidak lagi bisa menjamin pemerataan, maka jalan rusak di Lambitu bukan hanya masalah infrastruktur, tapi wujud nyata ketidakadilan yang telah dilembagakan.
Yang membuat ironi ini semakin dalam adalah bagaimana pemerintah daerah terus menggaungkan prinsip “pembangunan berbasis aspirasi” di ruang publik, sembari menutup mata pada wilayah yang justru paling konsisten menyuarakan aspirasi itu. Musrenbang yang semestinya menjadi instrumen koreksi dan komitmen demokratis telah berubah menjadi panggung repetisi frustasi rakyat Lambitu. Warga yang datang dengan harapan pulang dengan kekecewaan. Proposal yang disusun dengan ketelitian dijawab dengan pengabaian sistemik. Tahun berlalu, tetapi jalan tetap tak kunjung disentuh.
Pemerintah Kabupaten Bima dan DPRD-nya secara sadar membiarkan Lambitu terperosok dalam skema marginalisasi anggaran. Bukan karena tidak mampu membangun, tetapi karena mereka memilih untuk membangun di tempat lain di tempat yang menjanjikan imbal balik suara dan citra politik. Jumlah penduduk dan lokasi geografis dijadikan dalih untuk menjauhkan Lambitu dari akses pembangunan, padahal justru kondisi itu mestinya memicu kebijakan afirmatif. Bukankah mandat pemerataan menuntut prioritas pada yang paling rentan?
Lambitu terperangkap dalam logika pemetaan politik yang hanya menghargai suara yang bisa dikonversi menjadi kekuasaan. Maka wajar jika infrastruktur di sana dianggap sebagai beban, bukan sebagai kebutuhan rakyat. Padahal, setiap ruas jalan yang hancur adalah penolakan terang-terangan terhadap kehadiran negara di ruang-ruang yang tidak populer. Setiap genangan lumpur bukan hanya bahaya bagi pengendara, tapi juga simbol dari bagaimana kekuasaan menenggelamkan hak dasar masyarakat.
Narasi pembiaran ini tidak lahir dari ketidaksengajaan, tapi dari perencanaan politik yang dingin dan terukur. Ketika sistem hanya mendengarkan suara mayoritas dan menolak kebutuhan minoritas, maka demokrasi telah digantikan oleh algoritma elektoral. Lambitu bukan korban ketidaktahuan, tetapi korban dari pilihan kekuasaan yang mendefinisikan penting-tidaknya sebuah wilayah melalui bilangan suara.
Pemerintah boleh terus bicara soal pemerataan pembangunan. Tapi selama jalan di Lambitu tetap rusak, maka satu hal menjadi jelas: suara rakyat tidak otomatis menjadi keputusan politik. Dalam kasus Lambitu, suara mereka dijadikan latar, bukan isi. Dan selama hal ini dibiarkan, pembangunan hanya menjadi proses penghias kekuasaan bukan perbaikan kehidupan.