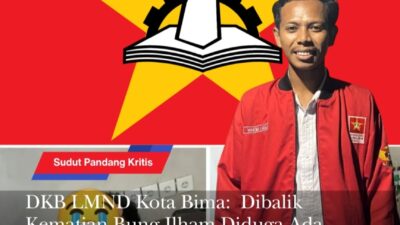Bima, 15 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) Ntb – Di tengah gegap gempita pembangunan daerah dan seruan keadilan anggaran di panggung politik lokal, ada satu wilayah yang tetap terdiam bukan karena warganya tak bersuara, tetapi karena sistem telah memutus saluran pendengaran ke arah mereka. Kecamatan Lambitu, dengan enam desa yang tersebar dan jumlah penduduk yang hanya sedikit di atas empat ribu jiwa, telah menjalani lebih dari dua dekade sebagai wilayah terasing dalam skema anggaran pembangunan Kabupaten Bima. Dan jawabannya mengapa jalan di sana belum juga diaspal bukan karena defisit fiskal, melainkan karena mereka tidak dianggap cukup penting secara politik.
Setiap tahun, masyarakat Lambitu bersuara melalui Musrenbang, menyampaikan dengan lugas dan konsisten satu permintaan: perbaikan infrastruktur jalan. Dari tingkat desa hingga ke meja Musrenbang kabupaten, tuntutan itu selalu menjadi prioritas. Jalan rusak bukan lagi soal kenyamanan, tapi sudah menyangkut keselamatan, akses pendidikan, pergerakan ekonomi, dan hak atas layanan kesehatan. Namun meski suara itu nyaring, realitas menunjukkan bahwa ia hanya dijadikan formalitas tahunan ditulis, dibahas sekilas, lalu dikubur di lemari birokrasi.
Politik anggaran di Kabupaten Bima seolah bergerak dengan kalkulator elektoral. Desa Ngali di Kecamatan Belo yang jumlah penduduknya lebih dari lima ribu jiwa melebihi gabungan seluruh warga Lambitu mendapat prioritas anggaran karena dianggap memiliki nilai strategis dalam peta suara. Sedangkan Lambitu, yang penduduknya tersebar dan desa-desa saling berjauhan hingga tiga kilometer, justru dianggap sebagai wilayah mahal tapi tidak menjanjikan keuntungan elektoral. Maka, pembangunan pun dipetakan bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan daya jual politik.
Logika anggaran seperti ini merampas hak konstitusional masyarakat Lambitu untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil. Mereka dibungkam bukan karena lemah, tapi karena sistem memilih untuk tidak mendengar. Infrastruktur jalan yang hancur menjadi lambang bagaimana kalkulasi suara lebih diutamakan daripada nilai kemanusiaan. Setiap lubang yang menganga di jalan Lambitu adalah lubang dalam prinsip pemerataan pembangunan yang dijanjikan negara. Dan selama pemerintah daerah menggunakan jumlah penduduk sebagai alat seleksi anggaran, maka di sanalah letak kekejaman paling sunyi dari sistem politik lokal kita.
Lambitu tidak kekurangan suara. Mereka kekurangan pendengar yang tulus. Dan selama jalan tetap rusak, lumpur tetap menyergap, dan kendaraan tetap tergelincir, maka sesungguhnya yang sedang tergelincir bukan hanya roda, tapi legitimasi kebijakan publik yang semestinya berpijak pada keadilan, bukan kalkulasi.Yang membuat kenyataan ini semakin menyakitkan adalah fakta bahwa warga Lambitu bukan sekadar menunggu.
Mereka aktif, terlibat, dan teguh menyuarakan kebutuhan mereka lewat jalur resmi dan demokratis. Musrenbang bukan sekadar dilewati, tetapi dimaksimalkan. Tahun demi tahun, enam desa di Lambitu mengirimkan utusan, menyusun proposal, dan mengajukan prioritas yang jelas: perbaikan jalan. Tapi bukannya direspons dengan kebijakan, suara itu justru diarsipkan, dijadikan bahan pelengkap rapat, tanpa satu pun langkah konkret di lapangan. Seolah partisipasi publik hanya dimanfaatkan sebagai legitimasi prosedural tanpa konsekuensi kebijakan.
Ketika pembangunan dikaitkan dengan efisiensi elektoral, maka wilayah seperti Lambitu akan selalu kalah sebelum bertanding. Pemerintah melihat penduduk bukan sebagai warga negara yang punya hak, tapi sebagai potensi suara dalam pemilu. Dan karena jumlahnya “terlalu kecil,” mereka dianggap tak punya nilai tawar. Hal ini menunjukkan secara terang bahwa kebijakan anggaran di Bima tidak dibangun atas semangat pemerataan, melainkan didikte oleh logika keuntungan politik. Sistem seperti ini menjadikan hak hidup masyarakat kecil sebagai barang yang bisa ditawar, bahkan ditinggalkan sepenuhnya.
Lebih ironis lagi, kondisi geografis Lambitu yang sulit justru digunakan sebagai dalih untuk menghindari pembangunan. Jarak antar desa yang berjauhan, kontur tanah yang berbukit, dan biaya logistik yang lebih tinggi dijadikan pembenaran untuk tidak membangun. Padahal, bukankah tantangan geografis justru mengharuskan kehadiran negara dengan intensitas yang lebih tinggi? Ketika mobil tidak bisa masuk karena jalan tertutup lumpur, ketika ambulans harus putar balik karena jurang dan genangan air, dan ketika anak-anak berjalan kaki berjam-jam ke sekolah, maka di sana bukan hanya pembangunan yang dibutuhkan, tapi kehadiran politik yang berpihak.
Narasi pembiaran ini bukan cerita satu dua tahun, melainkan pola yang berulang dan berakar. Ia mencerminkan watak kekuasaan yang hanya melihat pinggiran sebagai beban, bukan sebagai warga yang harus dilayani. Jalan di Lambitu tidak rusak karena tanahnya membangkang. Ia rusak karena pemerintah membiarkannya rusak. Dan setiap kali lumpur menelan roda kendaraan, yang sebenarnya tenggelam adalah harapan rakyat atas negara yang adil.