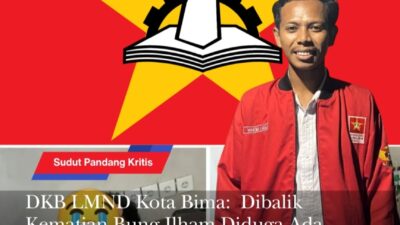Bima, 26 Juni 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) Ntb – Mari kita lakukan autopsi terhadap mayat paling segar di abad ke-21: nalar kritis. Waktu kematiannya tidak tercatat ia mati perlahan, setiap hari, dalam jutaan gesekan jari di atas layar kaca. Korban utamanya, ironisnya, bukanlah orang-orang bodoh yang tidak punya akses. Korban utamanya adalah kita: sang mahasiswa, sang agent of change yang kini lebih mirip agent of share, sang pewaris peradaban yang bangga karena bisa menemukan kutipan Foucault dalam 0,3 detik, namun tak punya daya tahan untuk membaca satu paragrafnya secara utuh.
Kita adalah generasi paling terinformasi dalam sejarah, sekaligus generasi yang paling rentan terhadap kebodohan massal. Inilah sertifikat kematian nalar kita, yang ditandatangani bukan dengan tinta, melainkan dengan cache dan cookies.
Kita telah melahirkan sebuah spesies baru: Homo Googlus. Makhluk ini memiliki akses informasi tak terbatas, namun dengan kapasitas pemahaman yang mendekati nol. Otaknya bukan lagi sebuah kuil pemikiran, melainkan sebuah gudang raksasa yang berantakan. Di dalamnya, bertumpuk fakta-fakta acak, potongan berita viral, meme, teori konspirasi dari TikTok, dan infografis warna-warni dari Instagram. Semua ada, semua bisa diakses.
Masalahnya? Sang pemilik gudang tak tahu apa-apa tentang isi barangnya. Ia tahu di mana meletakkan link, tapi tak pernah membuka isinya. Ia tahu cara mencari, tapi lupa cara mencerna. Kita menderita obesitas informasi, tetapi malnutrisi kearifan. Kita kekenyangan data mentah, namun kelaparan akan makna. Kecerdasan kita diukur dari seberapa cepat kita menemukan sesuatu, bukan dari seberapa dalam kita memahaminya.
Siapa pembunuhnya? Jangan buru-buru menunjuk jari ke diri sendiri. Pembunuhnya lebih subtil, lebih sistematis. Ia adalah arsitek tak terlihat dari penjara pikiran kita: sang algoritma.
Penjara paling nyaman adalah yang kita bangun sendiri, dan kita menghiasinya dengan notifikasi, likes, dan shares. Algoritma, sang sipir yang baik hati, setiap hari menyuapi kita dengan apa yang ingin kita dengar, bukan apa yang perlu kita tahu. Ia menciptakan sebuah gelembung filter (echo chamber) yang begitu nyaman, di mana setiap opini kita divalidasi, setiap bias kita diteguhkan. Di luar gelembung itu adalah dunia yang kompleks, penuh nuansa, dan melelahkan. Di dalam? Surga kepastian yang palsu.
Kita menyerahkan kedaulatan intelektual kita pada barisan kode yang dirancang untuk satu tujuan: menjaga perhatian kita selama mungkin. Kita mengira sedang menjelajahi dunia, padahal kita hanya berputar-putar di sebuah taman bermain digital yang dindingnya dicat menyerupai cakrawala.
Kita memegang seluruh Perpustakaan Alexandria di genggaman tangan, namun kita memilih untuk menghabiskan waktu di lorong toiletnya yang penuh coretan vandalisme. Kita adalah generasi yang paling berpotensi untuk menjadi generasi pencerahan baru, namun justru paling rentan untuk menjadi generasi pertama yang secara sukarela menyerahkan otaknya untuk dikendalikan.
Kita cerdas mengakses, tapi tumpul dalam merefleksi. Kita cepat menemukan, tapi lambat dalam merenung. Kita sibuk terkoneksi, tapi terputus dari esensi.
Jadi, sebelum jempolmu yang lincah itu kembali menekan tombol ‘share’ pada tulisan ini karena merasa “relate”, berhentilah sejenak. Tataplah layar hitam gawaimu, lihat pantulan wajahmu di sana.
Tanyakan pada pantulan itu: Informasi yang kau konsumsi hari ini, apakah itu membangun istana pemikiranmu, atau hanya menambah tumpukan sampah di gudang otakmu? Kapan terakhir kali kau membaca sesuatu yang membuatmu tidak nyaman, yang menantang seluruh keyakinanmu, dan kau bertahan sampai akhir?
Jangan sampai gelar sarjanamu kelak hanya menjadi penanda bahwa kau pernah terdaftar, bukan penanda bahwa kau pernah berpikir.